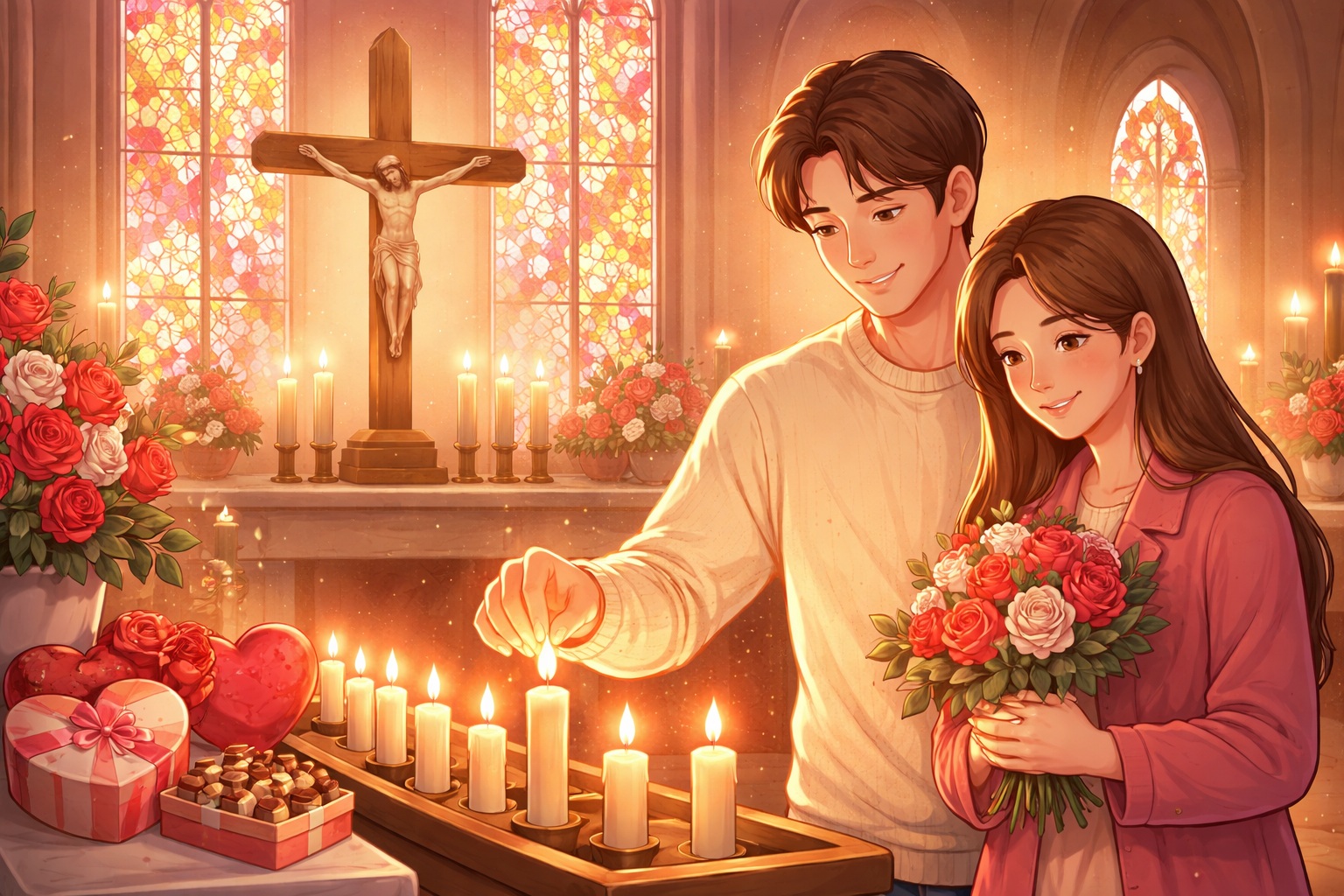Oleh Rikha Emyya Gurusinga
Katolikana.com—Setiap 14 Februari, etalase toko mendadak “berwarna”: bunga, cokelat, pita merah muda, diskon makan berdua. Di media sosial, cinta tampil rapi—seolah relasi yang sehat selalu punya caption manis dan foto yang pas.
Tapi di luar bingkai itu, banyak orang merayakan Valentine dengan perasaan yang lebih campur aduk: ada yang sedang LDR dan capek, ada yang baru putus, ada yang menikah tapi dingin-dingin saja, ada yang diam-diam merasa “kok hidupku sepi amat.” Kalau begitu, Valentine justru jadi cermin yang jujur: kita ini benar-benar mengasihi, atau hanya sedang mengejar sensasi “dicintai”?
Iman Katolik tidak anti romantisme. Perasaan cinta itu anugerah; ia bisa indah dan menghidupkan. Tetapi iman juga menolak menjadikan cinta sebatas rasa. Cinta yang matang adalah pilihan, latihan, dan kesetiaan—bukan sekadar momen.

Kasih yang tidak selalu manis
Kitab Suci tidak memberi kita definisi kasih yang “instan.” Santo Paulus malah menggambarkan kasih dengan kata-kata yang terasa seperti pekerjaan rumah: sabar, murah hati, tidak mencari keuntungan diri sendiri.
“Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri.” (1Kor 13:4–5)
Santo Paulusmenegur kita pelan-pelan: bila cinta hanya berpusat pada “aku merasa”, maka ketika rasa itu turun, cinta ikut tumbang.
Kasih menurut iman Kristiani bukanlah sesuatu yang instan atau egoistis. Ia bertumbuh dalam kesabaran, pengendalian diri, dan kesetiaan.
Cinta yang hanya bergantung pada perasaan akan mudah goyah ketika perasaan itu memudar. Sebaliknya, kasih yang berakar pada komitmen akan bertahan bahkan di tengah luka dan kekecewaan.
Karena itu, kasih Kristiani diuji bukan saat semuanya mudah, melainkan saat kita harus memilih tetap benar—meski tidak nyaman. Di titik inilah sabda Yesus terdengar tajam sekaligus realistis:
“Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.” (Yohanes 15:13)
Di sini, cinta mencapai puncaknya: memberi diri, bukan menuntut; berkorban, bukan menguasai. Inilah standar kasih Kristiani, yang jauh melampaui sekadar romantisme Valentine.
Namun, tidak semua orang diminta mati sebagai martir. Tetapi hampir semua orang diminta “mati kecil-kecilan” setiap hari: menahan ego, meminta maaf duluan, tidak memakai kata-kata untuk melukai, tidak memanipulasi pasangan, tidak ghosting ketika relasi mulai menuntut tanggung jawab. Kasih yang sejati sering tidak se-glamor hadiah Valentine, tapi jauh lebih menyelamatkan.
Santo Valentinus: bukan pangeran romantis
Valentine Day sering dihubungkan dengan Santo Valentinus, seorang martir dalam tradisi Gereja. Detail sejarahnya berkembang dalam berbagai kisah, tetapi arah pesannya jelas: ia dikenang karena kesetiaan—bukan karena “trik romantis.”
Kesetiaan ini penting untuk diingat, sebab budaya populer sering membingkai cinta sebagai sesuatu yang “mengalir begitu saja.” Padahal, dalam banyak relasi, yang paling sulit justru menjaga arah ketika godaan datang: godaan untuk mengambil jalan pintas, menyalahgunakan tubuh orang lain, atau memakai hubungan sebagai alat pemuas rasa sepi.
Di sini Valentine bisa bergeser dari pesta sentimental menjadi undangan untuk meneladan kasih yang berani: kasih yang tidak memuja perasaan, tetapi memuliakan martabat.
Eros yang dimurnikan, bukan ditindas
Gereja memahami bahwa manusia memiliki eros—cinta yang melibatkan hasrat, ketertarikan, romantisme. Itu wajar. Yang jadi masalah bukan erosnya, melainkan ketika eros berjalan sendirian tanpa agape—kasih yang memberi diri.
Paus Benediktus XVI mengingatkan bahwa keduanya tidak boleh dipisahkan: Deus Caritas Est menegaskan bahwa eros dan agape saling terkait (lih. Deus Caritas Est, art. 7). Artinya sederhana: cinta romantis akan sehat bila ia bergerak menuju pemberian diri yang tulus, bukan berhenti pada “aku ingin” dan “aku butuh.”
Kalau kita jujur, banyak luka relasi lahir karena cinta dipersempit menjadi transaksi: aku memberi perhatian supaya kamu membalas; aku setia selama kamu memenuhi ekspektasiku; aku bertahan selama kamu tidak merepotkanku. Logika seperti itu mungkin terlihat “normal”, tetapi diam-diam menggerogoti martabat.
Konsili Vatikan II menempatkan cinta pada horizon yang lebih luas: “Cinta sejati antara suami-istri mencakup kesejahteraan seluruh pribadi manusia” (Gaudium et Spes, art. 49). Maka, relasi yang benar bukan yang paling heboh, melainkan yang paling menghormati: menghormati tubuh, batin, kebebasan, juga masa depan orang yang kita cintai.
Di titik ini, Valentine layak menjadi momen refleksi yang serius: apakah cara kita mencintai membuat orang lain bertumbuh—atau justru membuatnya lelah, takut, dan kehilangan harga diri?
Valentine untuk semua panggilan hidup
Valentine sering dipersempit menjadi “hari orang pacaran.” Padahal dalam iman Katolik, panggilan mengasihi melekat pada semua orang: yang menikah, yang hidup membiara, imam, maupun yang melajang.
Orang yang belum punya pasangan tidak otomatis “kurang lengkap.” Mereka juga dipanggil mengasihi—sering kali dengan bentuk yang justru lebih sunyi: merawat orang tua, setia pada pelayanan, menemani yang kesepian, atau bekerja tanpa tepuk tangan.
Paus Fransiskus mengingatkan bahwa cinta bukan barang jadi. Ia dibangun, dirawat, dan diperjuangkan: Amoris Laetitia menegaskan bahwa cinta adalah sesuatu yang “dibangun hari demi hari” (lih. Amoris Laetitia, art. 134). Maka ukuran cinta bukan seberapa puitis ucapan kita, melainkan seberapa konsisten kita hadir, mendengar, dan setia pada kebaikan.
Merayakan Valentine secara realistis
Merayakan Valentine tidak salah. Yang perlu dijaga adalah arah. Kalau mau merayakannya secara Katolik, lakukan hal-hal yang kelihatan sederhana, tetapi sering paling berat:
- Doakan orang yang kamu cintai—bukan hanya agar ia “jadi milikmu”, tetapi agar ia bertumbuh dalam kebaikan.
- Minta maaf atau berdamai, bila ada relasi yang kamu biarkan retak terlalu lama.
- Tunjukkan perhatian pada mereka yang jarang diingat: lansia, teman yang sedang depresi, orang yang diam-diam berjuang sendirian.
- Bagi pasangan: bicarakan hal yang substansial—batas relasi, komitmen, cara menjaga kesucian, dan bagaimana kalian saling menolong agar makin dekat pada Allah, bukan makin jauh.
- Bagi yang melajang: rayakan juga kasih yang tidak romantis tapi nyata—persahabatan, keluarga, komunitas, pelayanan.
- Bagi keluarga, untuk memperkuat relasi yang mungkin mulai renggang;
- Bagi siapa pun, untuk menghadirkan kasih Allah kepada mereka yang kesepian, terluka, dan terpinggirkan.
Hadiah boleh ada. Namun hadiah terbaik sering bukan barang, melainkan kualitas hadir: mendengarkan tanpa menghakimi, tidak mempermainkan perasaan, tidak memakai tubuh orang lain, dan tidak menjadikan “cinta” sebagai alasan untuk melanggar martabat.
Bingkisan yang tahan selamanya
Apa bingkisan terbaik yang bis akita berikan kepada orang yang kita kasihi? Postingan di akun Instagram @katolik_garis_lucu menyentil kita: bunga akan layu, coklat akan ludes dan meleleh. Tapi kasih di salib akan tetap on dan tahan selamanya.
Valentine menempatkan kita di persimpangan: berhenti pada romantisme yang cepat lewat, atau melangkah ke kasih yang matang—kasih yang berakar pada Kristus, berani berkorban, dan setia menjaga martabat.
Pada akhirnya, cinta sejati tidak diukur dari seberapa meriah dirayakan, tetapi seberapa sungguh dihidupi—dengan kata, sikap, dan pilihan-pilihan kecil yang konsisten.
Selamat Hari Valentine!
Katolikana.com adalah media berita online independen, terbuka, dan berintegritas, menyajikan berita, informasi, dan data secara khusus seputar Gereja Katolik di Indonesia dan dunia.