
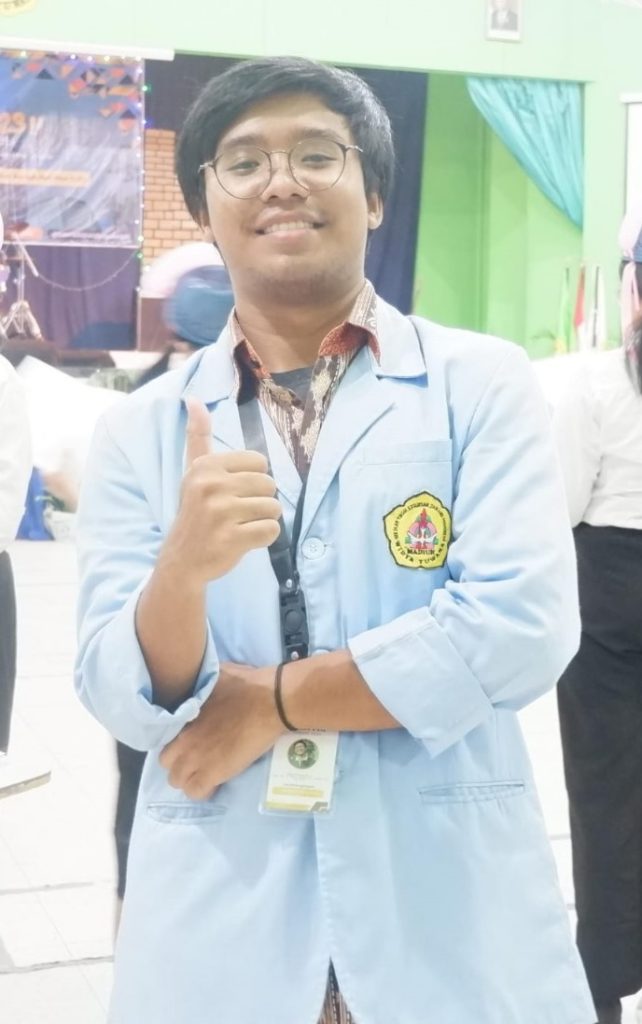
Oleh Michael Patrick Eka Satria
Katolikana.com – Korupsi di Indonesia bukan sekadar pelanggaran hukum; ia telah menjelma disorientasi moral yang merusak kepercayaan publik dan merapuhkan kelembagaan negara.
Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 versi Transparency.org menegaskan stagnasi, dengan skor Indonesia masih rendah dalam skala 0–100. Skor ini memotret tren kualitas tata kelola yang menurun dari waktu ke waktu, bukan sekadar peringkat.
Pada saat yang sama, publik menyaksikan dua sorotan yang menguji kompas moral elite.
Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta keterangan sejumlah pihak dalam penyelidikan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Whoosh—isu cost overrun dan tata kelola belanja proyek raksasa kembali dipertanyakan (Antara, 2025). Transparansi proses dan akuntabilitas keputusan menjadi prasyarat keadilan prosedural.
Kedua, lonjakan tunjangan reses anggota DPR ke kisaran Rp700 juta per anggota memantik kegusaran soal kepekaan sosial di tengah desakan efisiensi anggaran dan pelayanan publik (Republika, 2025). Kebijakan anggaran harus sanggup menjawab nalar keadilan, bukan sekadar lolos formalitas prosedur.
Dosa Sosial dan Kemunafikan: Kaca Mata Gereja
Gereja Katolik memandang korupsi sebagai dosa sosial yang melukai martabat manusia dan merusak kesejahteraan bersama.
Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, merujuk Kompendium Ajaran Sosial Gereja (KASG), secara eksplisit menyebut “korupsi politik” merusak fungsi negara, meretakkan relasi antara yang memerintah dan yang diperintah, serta menodai kepentingan umum (Vatican, 2006).
Karena itu, melawan korupsi bukan sekadar penegakan norma legal, melainkan tuntutan etis untuk memulihkan keadaban politik.
Di ranah rohani, Paus Fransiskus berulang kali mengingatkan bahwa korupsi bukan hanya perbuatan salah, melainkan keadaan jiwa yang membusuk—sebuah “pengapuran kebusukan” (varnished putrefaction) yang kerap terselubung kemunafikan (Paus Fransiskus, 2013).
Ia membedakan “pendosa” (yang masih mungkin bertobat) dari “orang korup” yang nyaman dalam munafik—peringatan keras terhadap apa pun yang membungkus kesalahan dengan prosedur.
Dalam horizon yang sama, Magisterium menegaskan politik sebagai panggilan luhur dan salah satu bentuk kasih yang paling tinggi—jika sungguh diarahkan pada bonum commune (kebaikan bersama).
Fondasi biblisnya eksplisit. “Jangan menerima suap, sebab suap membutakan orang yang melihat dengan jelas,” tegas Keluaran 23:8.
1 Timotius 6:10 mengingatkan “cinta uang adalah akar segala kejahatan”.
Matius 23 mengecam kemunafikan yang mempercantik rupa sambil membusukkan batin. Ketiga teks ini menegakkan pilar etika publik: kejujuran, integritas, dan keadilan sebagai kebajikan bersama.
Kerangka, Gereja: Jiwa
Secara kelembagaan, Trisula Pemberantasan Korupsi—penindakan, pencegahan, pendidikan—memberi kerangka strategis (Pusat Edukasi Antikorupsi KPK).
Namun, trisula ini tidak cukup tanpa pertobatan struktural: penguatan aturan benturan kepentingan, pelacakan TPPU dan pemulihan aset, open contracting, serta koordinasi lintas lembaga.
Tradisi sosial Gereja menegaskan kerusakan korupsi bukan hanya material, melainkan immaterial—merusak kualitas hidup bersama dan meruntuhkan kepercayaan sosial—maka tanggapannya harus menyentuh budaya dan karakter warga (Vatican, 2006).
Gereja dipanggil menjadi “pulau integritas”: komunitas yang menghidupi transparansi di paroki, sekolah, dan karya pastoral. Paling tidak ada tiga langkah konkret:
- Martyria (pewartaan yang membumi): Ajaran Sosial Gereja dan Kitab Suci dijadikan kurikulum hidup etika publik: simulasi kasus gratifikasi, whistleblowing, benturan kepentingan; literasi anggaran sekolah dan komunitas; dan pembiasaan due process dalam pengambilan keputusan (Kel 23:8; 1Tim 6:10; Mat 23).
- Diakonia (pelayanan yang akuntabel): Menerapkan standar transparansi: open book keuangan paroki/organisasi, audit internal, kanal pengaduan anonim, komite etik awam–imam. Ini sejalan dengan seruan Tahta Suci untuk “kewaspadaan ekstrem” melawan korupsi rohani dan struktural (Vatican, 2013).
- Koinonia (persekutuan yang berjejaring): Membangun kemitraan Gereja–kampus–LSM–KPK menjalankan Sula Pendidikan: kurikulum antikorupsi, klinik integritas, dan kampanye hidup sederhana sebagai anti-tesis “cinta uang”. Strategi ini sejalan dengan visi Trisula yang menempatkan pendidikan sebagai ujung yang sama pentingnya dengan penindakan dan pencegahan (Pusat Edukasi Antikorupsi KPK).
Menata Ulang Kompas Moral Negara
Kasus Whoosh dan polemik tunjangan reses menuntut keberanian untuk menyandingkan legalitas dengan legitimasi moral. Pemerintah dan parlemen wajib menunjukkan keteladanan etis: membuka data biaya proyek, metodologi penetapan tunjangan, dan impact evaluation atas manfaat publiknya; bersedia memangkas privilese yang tidak pro-poor; serta menjaga integritas kebijakan sosial agar tidak dibayangi rente.
Aparat penegak hukum mesti konsisten—dari penindakan hingga pemulihan aset—agar sinyal kepada pasar politik jelas: korupsi tidak menguntungkan. Perbaikan skor CPI hanya akan terjadi bila pembenahan sistem berjalan serempak dengan pembentukan habitus integritas.
Di level warga beriman, pesan Paus Fransiskus tetap relevan: politik adalah amal yang agung bila sungguh menyejahterakan yang paling lemah; sebaliknya, kemunafikan adalah bahasa orang korup.
Tugas komunitas beriman adalah merawat nalar publik yang jernih, menolak normalisasi gratifikasi, dan berpartisipasi aktif mengawasi anggaran—dari musyawarah lingkungan sampai forum kebijakan.
Dengan cara itu, Trisula KPK memberi kerangka; ajaran Gereja memberi roh; warga memberi teladan. Dari mimbar, kelas, rapat paroki hingga rapat parlemen—korupsi harus diperlakukan sebagai musuh bersama
Panggilan saya sebagai Katekis adalah panggilan untuk menjadi Nabi Kecil Kebenaran. Di tengah krisis disorientasi moral aparatur negara, tugas suci saya adalah melahirkan generasi baru yang tidak hanya cerdas secara spiritual, tetapi juga berintegritas tanpa kompromi, sehingga mereka kelak mampu memulihkan martabat bangsa dari penyakit korupsi. (*)
Penulis: Michael Patrick Eka Satria, Mahasiswa STKIP Widya Yuwana Madiun (Jurusan Teologi/Ilmu Pendidikan Agama Katolik).
Katolikana.com adalah media berita online independen, terbuka, dan berintegritas, menyajikan berita, informasi, dan data secara khusus seputar Gereja Katolik di Indonesia dan dunia.
